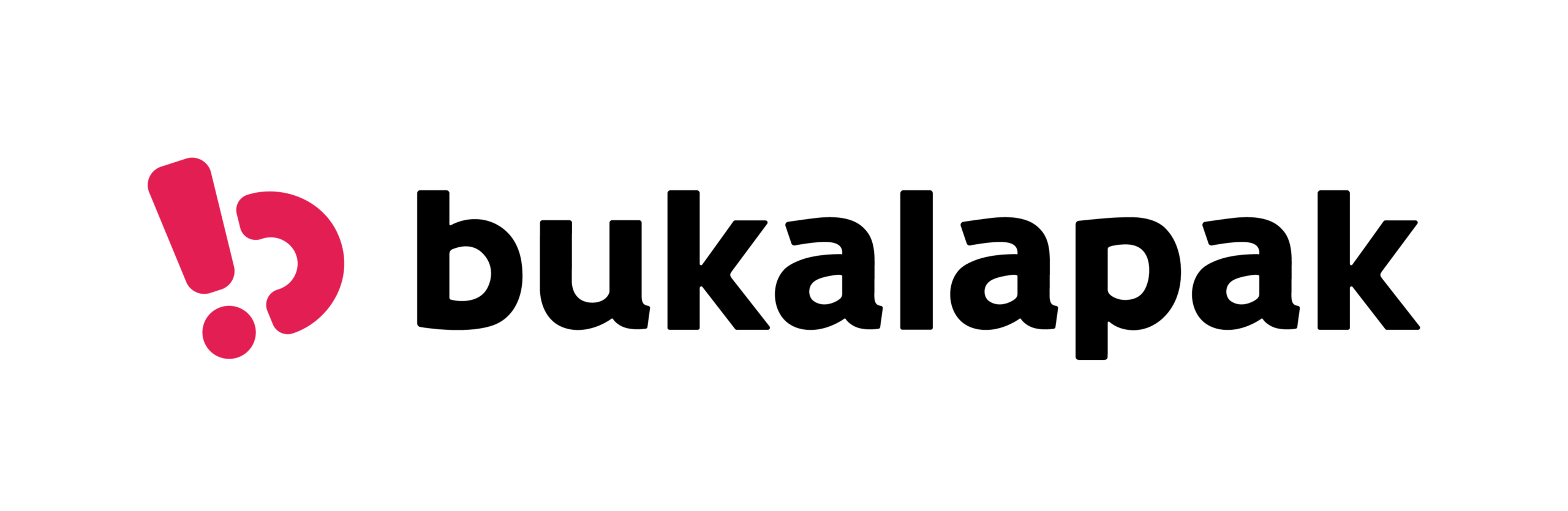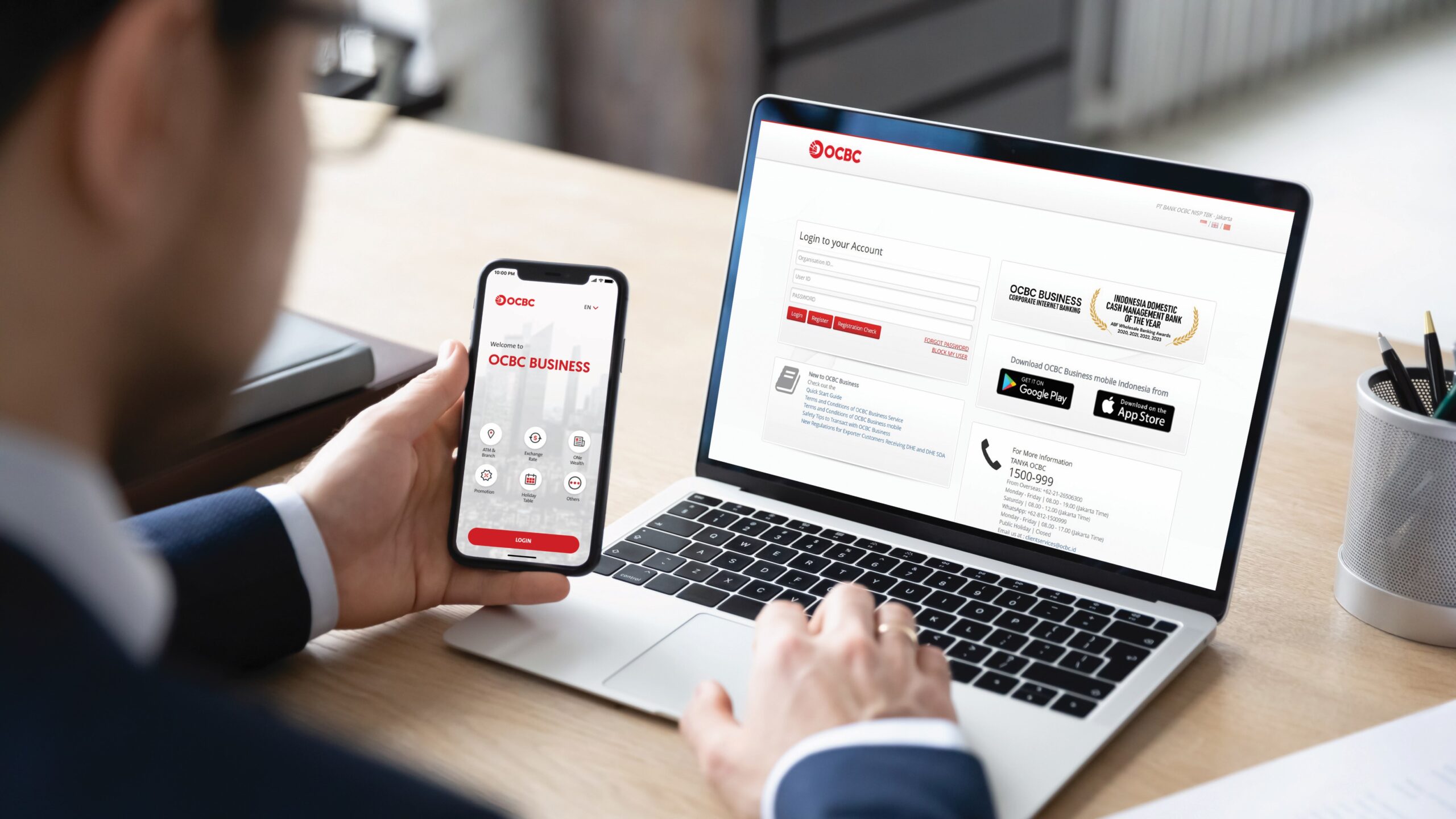Oleh: Wilson Arafat*
Krisis iklim bukan ancaman esok hari, melainkan kenyataan hari ini yang menuntut penataan ulang cara bangsa ini membangun dan melindungi bumi.
Hantaman bencana yang terjadi akhir-akhir ini, banjir bandang di Sumatra Barat, longsor di Sumatra Utara, dan gelombang pasang yang melanda wilayah pesisir, menegaskan bahwa krisis iklim telah nyata menjadi momok kerentanan sosial dan ekonomi di republik ini. Berbagai guncangan alam tersebut bukan lagi masalah ramalan cuaca, tetapi alarm kealpaan tata kelola risiko dalam pengelolaan pembangunan nasional.
Ironisnya, wacana krisis iklim ini sungguh bukanlah ‘makhluk’ baru sama sekali. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023) dalam laporannya menegaskan bahwa perubahan iklim akibat aktivitas manusia meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, yakni fenomena cuaca ekstrem yang mempengaruhi air, seperti banjir dan kekeringan. Lalu, Bank Dunia (2021) jauh hari telah mengingatkan bahwa sepanjang 1990-2021, Indonesia mengalami lebih dari 300 bencana alam, dan sekitar 70 persen di antaranya berkaitan langsung dengan variabilitas risiko iklim dan cuaca ekstrem.
Satu benang merah dapat ditarik bahwa risiko iklim telah menjadi risiko sistemik. Ini menembus batas wilayah, memicu kerugian sosial, ekonomi dan fiskal. Oleh karena itu, pengelolaan risiko iklim tidak cukup dilakukan parsial, tetapi membutuhkan tata kelola menyeluruh. Pada titik ini maka pengelolaan risiko iklim menjadi urgen dan krusial.
Dampak Risiko Iklim
Jika bangsa ini sembrono dan abai dalam mengelola risiko maka krisis iklim terus memperparah frekuensi dan intensitas bencana alam yang terjadi di Indonesia, dengan dampak yang sungguh luas. Laporan IPCC (2023) menjelaskan fenomena cuaca ekstrem semakin sering terjadi, memengaruhi sektor ekonomi dan bisnis.
Sebagai gambaran, variabilitas suhu dan curah hujan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, diperkirakan dapat mencapai kisaran empat persen dari PDB Indonesia pada tahun 2030 (Bank Dunia, 2021). Sementara, risiko perubahan iklim juga mengintai kesehatan masyarakat dan memperburuk penyebaran berbagai penyakit. Bahkan, laporan UNICEF (2022) memperkirakan bahwa perubahan iklim akan mengakibatkan 250.000 kematian per tahun akibat penyakit karena iklim ekstrem, dan sekaligus mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih parah lagi.
Biaya pemulihan pasca bencana dan kerugian fiskal negara pun semakin meningkat. Contoh nyata dapat terlihat pada saat bencana banjir menghantam Jakarta pada 2021, mengakibatkan kerugian hingga Rp12 triliun. Ini menunjukkan betapa besar kerugian yang dapat timbul akibat perubahan iklim, yang berpotensi menguras anggaran negara.
Vice versa, melalui pengelolaan risiko iklim secara cerdas akan membawa dampak kepada pembangunan nasional yang positif dan berkesinambungan. Investasi terkait adaptasi risiko iklim, seperti: pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem; penguatan sistem drainase dan pelindungan kawasan pesisir, mampu mengurangi kerusakan akibat bencana dan menghemat biaya pemulihan. Selain itu, adaptasi berbasis ekosistem, seperti: restorasi mangrove dan rehabilitasi hutan, dapat menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan, serta memperbaiki kondisi lingkungan secara lebih efektif dan berbiaya rendah.
Pendekatan tersebut juga dapat menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang sangat vital demi keberlanjutan ekonomi. Intinya, dengan mengelola risiko iklim dan kemudian menanamkannya kedalam berbagai kebijakan serta melibatkan juga berbagai kelompok rentan, seperti masyarakat pesisir dan petani kecil, maka kita secara bersama-sama dapat meningkatkan ketahanan sosial dan kesehatan, sekaligus mengurangi ketimpangan sosial yang telah ada selama ini.
Jadi, investasi dalam adaptasi iklim tidak hanya mengurangi kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengurangi beban fiskal negara. Alih-alih terus-menerus mengeluarkan anggaran besar untuk pemulihan pasca bencana, pengelolaan yang baik memungkinkan negara dapat menghemat anggaran negara dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.
Oleh karena itu, mengintegrasikan ESG risk dalam pengelolaan risiko iklim dapat menciptakan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini akan mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat mengubah tantangan perubahan iklim menjadi peluang untuk pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Risiko Iklim Sebagai Panglima
Untuk merealisasikan hal tersebut maka perlu ada kerangka yang menyeluruh dan terstruktur dalam mengelola risiko iklim, yang dapat diwujudkan melalui prinsip ESG. Kerangka ESG menawarkan pendekatan menyeluruh untuk mengelola risiko iklim. Pada pilar lingkungan, ESG mendorong pengelolaan risiko fisik dan transisi sebelum suatu proyek dimulai. Pada pilar sosial, ESG memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan yang paling terdampak bencana. Sementara, pada pilar tata kelola, pengambilan keputusan berbasis data analitik, risk assessment dan mengedepankan sisi akuntabilitas.
Pendekatan tersebut jauh melampaui sekadar norma dunia bisnis. ESG mencakup logika ekonomi rasional. Investasi adaptasi iklim memiliki manfaat ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang, dengan potensi menghemat biaya pemulihan yang besar, serta mengurangi ketergantungan negara pada anggaran darurat.
Studi World Resources Institute (2025) menunjukkan bahwa investasi terkait adaptasi iklim memiliki manfaat pengembalian besar, dengan setiap US$1 yang ditanamkan menghasilkan lebih dari US$10 dalam manfaat ekonomi sepanjang waktu sepuluh tahun.
Lebih dari menjadi kewajiban moral atau regulatif, adopsi ESG dan investasi adaptasi iklim bisa jadi pintu masuk ke peluang bisnis dan inovasi keuangan. Sebagai contoh, pasar karbon yang terintegrasi dapat membuka ruang bagi sektor swasta untuk mendanai ketahanan iklim, sementara tetap memperoleh insentif pasar yang kuat.
Menarik pula untuk dicermati, pemaparan dari United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI, 2024) yang mengungkapkan bahwa sektor keuangan global saat ini semakin mengakui pentingnya integrasi risiko iklim kedalam keputusan investasi dan kebijakan keuangan para pebisnis. Saat ini, hampir 70 persen sektor keuangan global sudah mengintegrasikan risiko iklim dalam kebijakan investasi mereka.
Di Indonesia, langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa sektor keuangan, yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian, ikut serta dalam mengatasi tantangan iklim. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penerapan ESG bukan hanya mitigasi risiko iklim, tetapi juga strategi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dalam era ekonomi rendah karbon kini.
Integrasi ESG dan adaptasi iklim dalam kerangka kebijakan bukan hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga memperkuat stabilitas sistem keuangan dan daya tahan ekonomi nasional. Adaptasi dan resilien iklim perlu menjadi bagian fundamental dari tata kelola risiko sektor keuangan agar kerugian akibat kejutan iklim tidak mengguncang anggaran negara atau perekonomian secara makro.
Investasi dalam sistem peringatan dini, pengelolaan air yang berkelanjutan, dan infrastruktur adaptif bisa mengurangi kerugian besar yang terjadi akibat bencana. Dengan langkah-langkah yang tepat, ESG menjadi instrumen penting demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Untuk mengantisipasi risiko iklim ini, sejumlah langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, sektor keuangan dan industri berisiko tinggi perlu mewajibkan untuk climate-risk disclosure. Penilaian risiko banjir, kekeringan, abrasi dan skenario iklim harus menjadi bagian dari setiap keputusan investasi. Menurut World Bank (2021), lebih dari 40 persen investasi di Indonesia perlu dialokasikan untuk infrastruktur yang berkelanjutan dan tahan iklim.
Kedua, investasi publik perlu diarahkan pada infrastruktur adaptif dan solusi berbasis alam. Restorasi hutan, rehabilitasi daerah aliran sungai, perlindungan pesisir berbasis mangrove, serta penguatan sistem peringatan dini terbukti lebih efektif dan berbiaya rendah dibandingkan pendekatan yang konvensional.
Ketiga, pembaruan tata ruang menjadi kunci. Data ilmiah terkini harus menjadi dasar perencanaan yang disusun secara holistik dan sistematis sehingga zona rawan tidak lagi dihuni oleh permukiman padat penduduk ataupun fasilitas yang minim dan kritis. Keempat, standar ESG harus diintegrasikan dalam kebijakan anggaran, perizinan, bisnis dan investasi swasta. Dengan demikian, pengelolaan risiko menjadi bagian dari sistem, bukan respons setelah bencana.
Perubahan iklim telah memperlihatkan bahwa risiko tidak lagi bersifat linear. Dampaknya semakin kompleks dan berlapis, mempengaruhi kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, stabilitas fiskal, hingga keberlanjutan bisnis dan ekonomi. Sementara, ESG memberikan kerangka untuk merespon tantangan tersebut secara komprehensif, sistematis dan terukur.
Namun demikian, penerapannya membutuhkan keputusan politik (political will) dan institusional yang kuat secara kolektif. Jika langkah-langkah mitigasi, adaptasi dan pengelolaan risiko iklim terus ditunda maka biaya yang harus ditanggung masyarakat dan negara akan semakin membesar.
Karena itu, menempatkan pengelolaan risiko iklim sebagai panglima dalam pembangunan bukan hanya pilihan kebijakan, melainkan sudah menjelma menjadi suatu keharusan moral dan strategis. Now or never!
Tulisan ini adalah pendapat pribadi
*Penulis adalah GRC specialist, bankir senior, pengalaman 28 tahun di industri perbankan, spesialisasi GRC, ESG & Manajemen Transformasi.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News